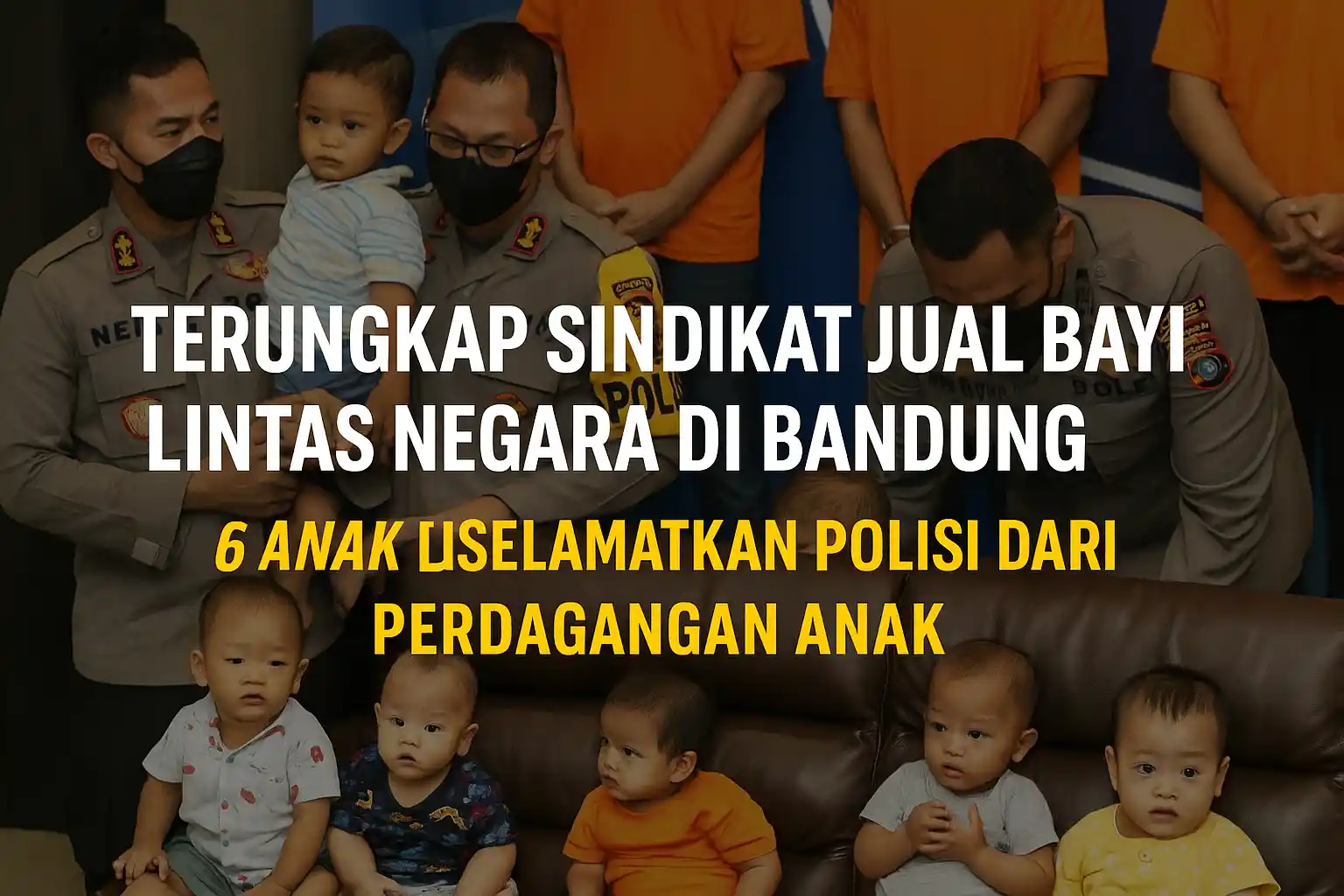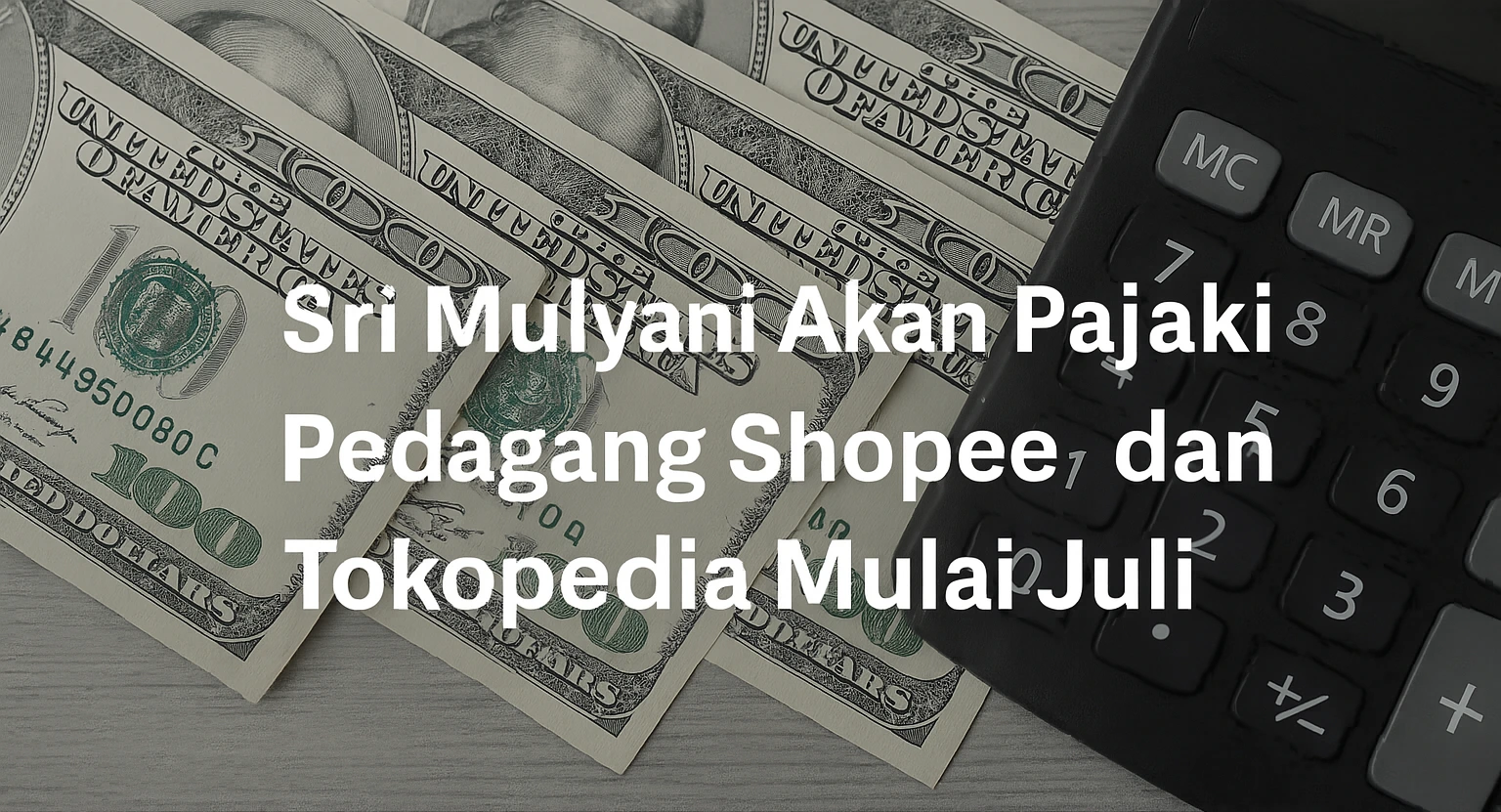Dalam pernyataan terbaru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memicu kontroversi dengan menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mewajibkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Ia membuka peluang agar kepala daerah bisa dipilih kembali lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pernyataan ini mengundang perdebatan sengit, baik dari kalangan politisi, akademisi, hingga masyarakat sipil.
Penjabaran Tito Karnavian: Dasar Konstitusional
Tito menyebut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar pernyataannya. Pasal tersebut berbunyi:
“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
Menurut Tito, frasa “dipilih secara demokratis” tidak serta merta berarti harus lewat pemilihan langsung oleh rakyat. Ini membuka ruang interpretasi bahwa pemilihan melalui DPRD pun masih bisa dianggap demokratis selama prosesnya transparan, akuntabel, dan representatif.
Konteks Historis: Kembali ke Masa Orde Baru?
Sebelum reformasi, pemilihan kepala daerah memang dilakukan oleh DPRD. Namun, sejak diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004, Indonesia beralih ke sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan akuntabilitas kepala daerah, serta mempersempit ruang negosiasi politik elitis di balik layar.
Gagasan untuk mengembalikan pemilihan lewat DPRD membuat sebagian pihak khawatir akan potensi kemunduran demokrasi dan kembali ke sistem sentralistik yang tidak partisipatif.
Reaksi Politik dan Masyarakat Sipil
Sejumlah politisi mulai merespons wacana ini. Partai Golkar, misalnya, menyatakan keterbukaan terhadap opsi tersebut asalkan tetap mengedepankan keterlibatan publik seperti debat terbuka atau kampanye terbatas bagi calon kepala daerah.
Namun, kelompok masyarakat sipil dan pengamat demokrasi menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa menjadi jalan mundur demokrasi Indonesia. Beberapa menyebut bahwa kembalinya pemilihan lewat DPRD dapat membuka peluang dominasi oligarki lokal dan menurunkan legitimasi pemimpin daerah.
Apakah Perubahan Ini Memungkinkan?
Perubahan mekanisme pilkada tidak bisa dilakukan secara sepihak. Diperlukan:
- Revisi Undang-Undang Pilkada (UU No. 10/2016)
- Dukungan politik mayoritas di DPR
- Konsultasi publik dan uji materi di Mahkamah Konstitusi jika ada penolakan
Jika disepakati, bukan tidak mungkin pemilu kepala daerah via DPRD bisa diterapkan mulai 2029, atau bahkan lebih cepat jika ada percepatan legislasi.
Menuju Pilkada Versi Baru?
Pernyataan Tito membuka diskusi serius tentang masa depan demokrasi lokal Indonesia. Di satu sisi, efisiensi anggaran dan stabilitas politik menjadi nilai tambah. Namun di sisi lain, hilangnya suara rakyat secara langsung adalah risiko besar yang tidak boleh diremehkan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan sistem politik dilakukan secara inklusif, transparan, dan berbasis pada semangat demokrasi substansial, bukan sekadar formalitas prosedural.
Wacana Tito Karnavian Tuai Pro-Kontra

1. Kemunduran Demokrasi Langsung
Salah satu capaian utama era reformasi adalah penguatan demokrasi langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan manifestasi dari prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mengembalikan pemilihan ke DPRD dianggap oleh banyak kalangan sebagai kemunduran signifikan menuju sistem demokrasi prosedural tanpa partisipasi nyata.
2. Rentan Politik Transaksional dan Oligarki Lokal
Ketika pemilihan diserahkan pada segelintir anggota DPRD, risiko politik uang dan transaksi kekuasaan meningkat drastis. Dalam banyak kasus, DPRD bukan institusi steril dari praktik koruptif. Mekanisme tertutup ini justru membuka peluang elit lokal untuk mempertahankan kekuasaan melalui kesepakatan politik yang tidak transparan.
3. Mematikan Akuntabilitas Publik
Pemimpin daerah yang dipilih langsung memiliki ikatan moral dan politik dengan konstituennya. Ketika kepala daerah dipilih DPRD, maka loyalitas politik cenderung bergeser ke partai dan elit legislatif, bukan kepada masyarakat. Ini berpotensi membuat kepala daerah abai terhadap aspirasi warga karena tidak bergantung pada suara publik.
4. Membungkam Ruang Pendidikan Politik
Pemilu langsung bukan hanya soal memilih, tetapi juga sarana pendidikan politik rakyat. Masyarakat belajar menilai program, membandingkan visi-misi, hingga berani bersikap politik. Jika model ini dihapus, maka ruang pembelajaran demokrasi akan menyempit, terutama bagi generasi muda.
5. Efisiensi Bukan Alasan Sah untuk Mengurangi Demokrasi
Argumen utama yang sering dipakai adalah tingginya biaya pilkada langsung. Namun, biaya demokrasi tidak bisa hanya dihitung secara fiskal. Korupsi di tingkat DPRD juga tak kalah mahal bagi negara. Daripada mengubah sistem, solusi lebih rasional adalah reformasi pembiayaan dan transparansi kampanye.
Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD harus dilihat sebagai tanda bahaya bagi demokrasi Indonesia. Dalam iklim politik yang masih sarat patronase dan oligarki, sistem ini lebih mudah dimanipulasi oleh kekuatan politik elit.
Demokrasi memang mahal dan penuh risiko, namun solusinya bukan dengan mengurangi peran rakyat, melainkan memperbaiki sistemnya dari dalam.
🔎 Akhir dari Kritik:
Lebih murah memang, asal suara bisa dibeli di ruang rapat… ya kan?